 Sutradara: Gus van Sant
Sutradara: Gus van SantSkenario: Dustin Lance Black
Pemain: Sean Penn, James Franco, Josh Brolin, Emile Hirsch
Jauh sebelum Obama menjadi kosakata dunia, nun di San Francisco pada 1970-an ada Harvey Milk. Milk identik dengan sebongkah harapan, yang meniupkan roh kepada San Francisco—dan Amerika—tentang persamaan hak. Pidatonya tentang harapan kaum gay yang mengalami diskriminasi pada 1970-an di Amerika, keberaniannya mencalonkan diri sebagai anggota dewan penasihat di pemerintah daerah adalah terobosan pada masanya.
Kisah hidup tokoh politik yang tewas ditembak karena memperjuangkan hak kaum gay ini sudah pernah kita saksikan dalam film dokumenter The Times of Harvey Milk karya Robert Epstein (1984). Kali ini sutradara Gus van Sant mengangkat Milk sebagai orang yang tak kunjung capek untuk terus berpolitik, dan sebagai seorang pribadi.
Dengan warna-warni suram yang memberikan aroma tahun 1970-an, Van Sant memulai filmnya saat Harvey Milik (Sean Penn) berbicara di depan mikrofon merekam suaranya sendiri, soliter, tentang kehidupannya. Dia sudah diancam berkali-kali oleh berbagai jenis makhluk. Tapi Milk tak gentar. Kalimatnya, ”If a bullet should enter my brain, let the bullet destroy every closet door,” menjadi kalimat yang membius hingga kini untuk tidak jatuh cengeng serta terus melawan kebijakan dan perlakuan yang diskriminatif.
Kamera kemudian meloncat pada pertemuan pertama Milk dengan Scott Smith (James Franco, yang tampil hangat, tampan, dan penuh simpati). Mereka pindah dari New York ke San Francisco. Di Jalan Castro, mereka mendirikan sebuah toko kamera yang lebih banyak berfungsi sebagai tempat nongkrong para aktivis gay yang ikut membicarakan dan merencanakan perlawanan bagi kebijakan yang diskriminatif.
Van Sant, yang pernah menghasilkan film-film dengan aroma indie, seperti My Own Private Idaho dan Drugstore Cowboy, serta film yang lebih masuk kategori mainstream, seperti To Die For dan Good Will Hunting, terlihat gairahnya mencapai titik tertinggi dalam film Milk. Sean Penn jelas telah hilang total karena dia telah menjelma menjadi sosok Harvey Milk. Suara, bahasa tubuh, hingga kemesraannya dengan sang kekasih yang bukan persoalan erotisme belaka tetapi lebih menunjukkan intimasi yang mengharukan itu menunjukkan Penn adalah aktor kelas satu yang memang layak mendapatkan Oscar tahun ini sebagai aktor terbaik.
Pemain pendukungnya antara lain Josh Brolin, yang tampil sebagai Dan White, lawan politik yang memiliki gejolak yang ganjil, antara ”membenci” dan ”menyukai” geng Milk ini; Emile Hirsch, yang tampil sebagai gay remaja yang semula tengil dan akhirnya bergabung dalam perjuangan ini; dan James Franco, kekasih Milk yang setia tetapi tak tahan hidup didera mesin politik.
Milk tewas ditembak. Ini sudah diketahui sejak awal cerita, karena Van Sant bukan mencoba membuat sebuah cerita thriller-suspense. Dia ingin menampilkan bagaimana seorang aktivis-politikus gay yang sempat hidup sebentar itu, yang tahu bahwa dirinya akan menjadi sasaran peluru, lebih peduli agar suaranya bisa didengar.
Anda merasa persoalan gay bukan urusan kita? Cerita yang terlalu jadul? Persoalan diskriminasi (terhadap perbedaan orientasi seksual, warna kulit, gender, atau apa pun) adalah persoalan semua orang dan masih menjadi problem besar saat ini.
(Dari Majalah TEMPO Edisi 02/XXXVIII 02 Maret 2009)
Kisah hidup tokoh politik yang tewas ditembak karena memperjuangkan hak kaum gay ini sudah pernah kita saksikan dalam film dokumenter The Times of Harvey Milk karya Robert Epstein (1984). Kali ini sutradara Gus van Sant mengangkat Milk sebagai orang yang tak kunjung capek untuk terus berpolitik, dan sebagai seorang pribadi.
Dengan warna-warni suram yang memberikan aroma tahun 1970-an, Van Sant memulai filmnya saat Harvey Milik (Sean Penn) berbicara di depan mikrofon merekam suaranya sendiri, soliter, tentang kehidupannya. Dia sudah diancam berkali-kali oleh berbagai jenis makhluk. Tapi Milk tak gentar. Kalimatnya, ”If a bullet should enter my brain, let the bullet destroy every closet door,” menjadi kalimat yang membius hingga kini untuk tidak jatuh cengeng serta terus melawan kebijakan dan perlakuan yang diskriminatif.
Kamera kemudian meloncat pada pertemuan pertama Milk dengan Scott Smith (James Franco, yang tampil hangat, tampan, dan penuh simpati). Mereka pindah dari New York ke San Francisco. Di Jalan Castro, mereka mendirikan sebuah toko kamera yang lebih banyak berfungsi sebagai tempat nongkrong para aktivis gay yang ikut membicarakan dan merencanakan perlawanan bagi kebijakan yang diskriminatif.
Van Sant, yang pernah menghasilkan film-film dengan aroma indie, seperti My Own Private Idaho dan Drugstore Cowboy, serta film yang lebih masuk kategori mainstream, seperti To Die For dan Good Will Hunting, terlihat gairahnya mencapai titik tertinggi dalam film Milk. Sean Penn jelas telah hilang total karena dia telah menjelma menjadi sosok Harvey Milk. Suara, bahasa tubuh, hingga kemesraannya dengan sang kekasih yang bukan persoalan erotisme belaka tetapi lebih menunjukkan intimasi yang mengharukan itu menunjukkan Penn adalah aktor kelas satu yang memang layak mendapatkan Oscar tahun ini sebagai aktor terbaik.
Pemain pendukungnya antara lain Josh Brolin, yang tampil sebagai Dan White, lawan politik yang memiliki gejolak yang ganjil, antara ”membenci” dan ”menyukai” geng Milk ini; Emile Hirsch, yang tampil sebagai gay remaja yang semula tengil dan akhirnya bergabung dalam perjuangan ini; dan James Franco, kekasih Milk yang setia tetapi tak tahan hidup didera mesin politik.
Milk tewas ditembak. Ini sudah diketahui sejak awal cerita, karena Van Sant bukan mencoba membuat sebuah cerita thriller-suspense. Dia ingin menampilkan bagaimana seorang aktivis-politikus gay yang sempat hidup sebentar itu, yang tahu bahwa dirinya akan menjadi sasaran peluru, lebih peduli agar suaranya bisa didengar.
Anda merasa persoalan gay bukan urusan kita? Cerita yang terlalu jadul? Persoalan diskriminasi (terhadap perbedaan orientasi seksual, warna kulit, gender, atau apa pun) adalah persoalan semua orang dan masih menjadi problem besar saat ini.
(Dari Majalah TEMPO Edisi 02/XXXVIII 02 Maret 2009)


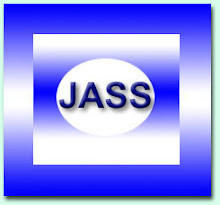



1 Komentar:
Sean Penn?
Gilaa!
Edan!
Total lo maen....!Layak diganjar oscar!
Awas nti kayak Al Pacino di Cruising!
Posting Komentar